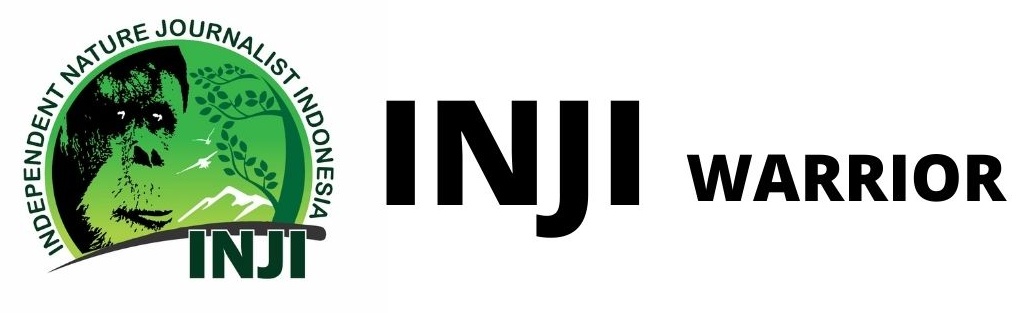Papua-Di tengah sumber daya alam yang melimpah, Papua hingga saat ini masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan yang menjeratnya. Berbagai upaya digencarkan untuk mendorong provinsi tersebut maju seperti pemberian Dana Otonomi Khusus. Namun, program itu tidak banyak mengubah keadaan provinsi tersebut.
Sejak 2001, pemerintah pusat telah mengirimkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Catatan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), pemerintah telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 138,65 triliun melalui skema tersebut hingga 2021 lalu. Limpahan dana dalam jumlah besar tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan, sesuai dengan teori big push dalam ekonomi.
Namun, INDEF menilai bahwa upaya tersebut belum berhasil. Dana besar yang digelontorkan pemerintah pusat tidak berdampak signifikan pada upaya memajukan Papua.
“Dana Otsus di Papua belum berhasil menjadi big push. Dia hanya meningkatkan APBD, hanya meningkatkan PDRB perkapita yang signifikan secara statistik,” kata Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF, dalam diskusi dan diseminasi laporan riset: Kutukan Sumber Daya Alam di Tanah Papua, pada Senin (19/12).
INDEF bersama Greenpeace telah melakukan penelitian mendalam terkait fenomena kekayaan sumber daya alam yang besar di Papua, yang tidak mampu mendorong kesejahteraan di wilayah itu. Dalam ilmu ekonomi, kondisi tersebut bagaikan ironi yang dikenal sebagai kutukan sumber daya alam.
Secara sederhana, istilah itu bermakna negara atau wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, khususnya yang tidak terbarukan seperti minyak dan tambang, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih lambat.
Sepanjang penerapan dana Otsus, sejumlah parameter seperti kemiskinan, kesehatan hingga pendidikan di Papua memang mengalami perbaikan, tetapi pencapaiannya masih jauh di bawah capaian provinsi lain.
“Harusnya, dengan uang yang sedemikian banyak, bisa lebih tinggi. Sehingga kesimpulannya, bahwa terjadi kutukan sumber daya alam di Papua pada sektor pendidikan, hutan, kesehatan, sanitasi dan angka harapan hidup,” papar Berly.
Secara statistik dan kuantitatif, lanjut Berly, kutukan sumber daya alam di Papua terjadi di luar persoalan dana. Di dalam angka, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memang meningkat.
“Tetapi dampaknya ke manusia ada tidak? Itu yang perlu diubah di Otsus jilid dua, sehingga dampaknya berkesinambungan. Karena kalau hanya uang, uangnya dari Otsus bisa berubah. Dari tambang bisa habis. Tapi untuk manusia, kalau sudah dibangun, dia akan terus membawa manfaat selama satu generasi atau lebih,” papar Berly.
Kehilangan Hutan Alam
Salah satu persoalan mengenai sumber daya alam di Papua adalah hilangnya wilayah hutan secara masif dalam dua dekade terakhir. Kondisi tersebut jelas merugikan karena hutan di Papua termasuk ke dalam tiga wilayah di dunia dengan kondisi hutan yang cukup baik di mana Papua bersanding dengan Amazon dan Kongo.
“Riset Greenpeace, dalam dua dekade terakhir tanah Papua kehilangan 641 ribu hektar hutan alam, dan kalau kita lihat, deforestasi meningkat sejak tahun 2012, puncak kehilangan terluasnya di tahun 2015,” kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, dalam diskusi yang sama.
Kiki memaparkan data penelitian dari Global Forest Watch, Universitas Maryland, Amerika Serikat, yang mencatat bahwa tahun 2001-2020 provinsi Papua kehilangan 438 ribu hektar hutan. Lima kabupaten dengan deforestasi terluas adalah Merauke, Boven Digul, Nabire, Mimika dan Mappi. “ Di Merauke tercatat 92 ribu hektar, sedangkan di Boven Digul 69 ribu hektar,” rincinya.
Sementara di provinsi Papua Barat, hutan alam yang hilang seluas 203 ribu hektar, dengan lima kabupaten tertinggi adalah Fak-Fak, Teluk Bintuni, Sorong, Manokwari dan Kaimana.
Industri ekstraktif yang belakangan berpindah ke Papua, dan pembentukan provinsi-provinsi baru menjadi faktor yang mempengaruhi deforestasi.

Pemandangan dari area pertambangan tembaga dan emas Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia, di Papua, dalam foto yang diambil pada 19 September 2015. (Foto: Antara via Reuters)
Kiki menjelaskan bahwa kini terdapat empat jenis perizinan usaha yang berdampak besar pada deforestasi di Papua. Keempat usaha tersebut adalah pertambangan, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 20 persen dari seluruh tanah Papua, telah dibebani izin atau konsesi dari empat jenis konsesi tersebut, kata Kiki.
“Kalau kita lihat peta wilayah pertambangan Papua, maka 80 persen wilayah tanah Papua itu bagian dari wilayah usaha pertambangan. Artinya, bahwa wilayah Papua ini sudah dipetakan, ada potensi, dia masuk dalam wilayah usaha pertambangan, meskipun itu masih jauh, tetapi ini berpotensi,” lanjutnya.
Saat ini, terdapat 1,88 juta hektar perkebunan sawit di Papua, dengan rincian 1,3 juta hektar berada di provinsi Papua dan 516 ribu hektar di Papua Barat. Perkebunan sawit terbesar di dua provinsi tersebut berada di kabupaten Merauke, Boven Digul, Mappi, Teluk Bintuni dan Sorong.
Posisi Masyarakat Adat
Merespons kondisi mengenai kutukan sumber daya alam Papua, Antropolog dari Universitas Cenderawasih, Papua, Gerda Numberi menyebutkan bahwa terdapat tiga pihak utama yang mampu membawa provinsi tersebut keluar dari jerat kutukan itu.
“Pertama, itu dari pemilik sumber daya alam itu sendiri, yaitu masyarakat adat. Kedua, dari pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan juga pusat. Ketiga itu, adalah para pihak ketiga atau korporasi yang biasanya menggunakan, memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.
Namun sayangnya, ketiga pihak itu, lanjut Gerda, memiliki konsep pemanfaatan hutan dan sumber daya alam yang berbeda-beda.

Masyarakat adat Lembah Grime Nawa saat menyampaikan aspirasinya terkait tanah adat di depan kantor Bupati Jayapura, pada 7 September 2022. (Foto: Courtesy of LBH Papua)
Pendapat senada disampaikan Filep Wamafma, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua. Dari tiga pihak itu, masyarakat adat Papua berprinsip bahwa alami menunjang, memberi, dan melindungi kehidupan.
“Kalau pemerintah tidak. Kalau investor tidak. Alam itu memberikan modal yang besar, kekayaan yang besar bagi negara. Alam menyediakan sumber pendapatan daerah yang tinggi, alam mendatangkan investasi yang besar,” ujar Filep.
Kondisi tersebut kemudian menyebabkan pertentangan antara kepentingan investor, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya, lanjut Filep, pemerintah lebih condong mendukung kepentingan investasi.
Berdampak pada Separatisme
Ketidakselarasan antara pemerintah dan masyarakat menciptakan kondisi yang tidak aman yang dapat berdampak panjang. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Cahyo Pamungkas mengatakan, kerusakan lingkungan akan menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat adat Papua. Kerusakan itu sendiri diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada kapitalisme, yang didorong oleh perusahan dan pemerintah sendiri.
“Ini akan cenderung memunculkan marjinalisasi dan distrust dari masyarakat adat Papua, dan pada akhirnya akan mendorong konflik pemisahan diri atau konflik separatisme. Sehingga antara kerusakan lingkungan, human insecurity dan konflik separatis saling terkait,” jelas Cahyo.
Dia menambahkan, jika alam dan hutan Papua rusak, masyarakat adat menjadi rawan. Kondisi ini menghadirkan perasaan tidak menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
“Dan mereka memiliki impian untuk kembali ke rumah lama, rumah tua mereka, yaitu kawasan Melanesia, atau ingin memisahkan diri dari Indonesia,” tegasnya.
Source: VOA Indonesia